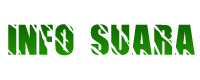Oleh : Dr. Arsalim
(Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara)
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID-Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyinggung fenomena global "My Country First"—sebuah pergeseran arah kebijakan nasional dari internasionalisme ke nasionalisme.
Istilah ini bukan sekadar jargon populis, tetapi cerminan dari perubahan mendalam dalam dinamika geopolitik dan ekonomi dunia. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini perlu dianalisis secara mendalam agar kebijakan nasional tetap relevan dan strategis.
Kelahiran Kembali Nasionalisme
Setelah era globalisasi yang menguat sejak 1990-a dan dekade 2010-an, kita menyaksikan munculnya kembali nasionalisme politik dan ekonomi. Di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump mengusung slogan "America First" sebagai janji untuk mengutamakan pekerja dan industri domestik.
Kebijakan ini diwujudkan melalui perang dagang dengan China, penarikan dari perjanjian internasional seperti Paris Agreement dan pembatasan imigrasi. Brexit di Inggris adalah manifestasi lain dari nasionalisme modern, di mana suara mayoritas rakyat Inggris memilih keluar dari Uni Eropa demi mengembalikan kedaulatan nasional.
Di India, kebijakan "Make in India" bertujuan memperkuat manufaktur domestik, sementara di China, strategi "dual circulation" menekankan penguatan pasar domestik tanpa melepaskan keterlibatan global.
Fenomena "My Country First" dapat dianalisis melalui dua lensa besar dalam hubungan internasional: Pertama; Realisme: Dalam teori realisme klasik dan neorealisme, negara adalah aktor rasional yang berusaha memaksimalkan kepentingannya dalam sistem internasional yang anarkis.
Dalam kondisi global yang tidak stabil seperti pandemi, perubahan iklim, krisis panga, negara cenderung menarik diri untuk fokus ke dalam, memperkuat otonomi nasional. Dalam konteks ini Hans J. Morgenthau, dalam bukunya “Politics Among Nations (1948)”, menyatakan bahwa politik internasional diatur oleh hukum kekuasaan dan kepentingan nasional.
Kedua; Nasionalisme Ekonomi (Economic Nationalism). Teori ini menyatakan bahwa negara seharusnya melindungi industri strategis dan tidak tergantung pada pasar global. Dalam praktiknya, ini berarti penerapan tarif, pembatasan ekspor bahan mentah, dan subsidi untuk industri dalam negeri.
Alexander Hamilton di Amerika Serikat yang dianggap pelopor nasionalisme ekonomi melalui usulan Report on Manufactures (1791) menyatakan bahwa tarif tinggi harus didorong untuk melindungi industri dalam negeri. Namun, pendekatan ini bisa mengarah ke proteksionisme ekstrem jika tidak dikelola dengan cermat.
Gagasan nasionalisme ekonomi kembali muncul kuat pada abad ke-21 dengan tokoh-tokoh politik seperti Donald Trump, Viktor Orbán, dan Narendra Modi yang mengusung proteksionisme modern.
Ketiga; Neoliberalisme Institusional: Sebagai kontra-argumen, teori ini menekankan pentingnya kerja sama internasional melalui institusi multilateral. Keberhasilan penanggulangan pandemi, misalnya, sangat bergantung pada kolaborasi lintas negara dan pertukaran teknologi.
Robert Keohane dan Joseph Nye adalah dua tokoh utama. Mereka mengembangkan teori ini sebagai kritik terhadap realisme, sambil tetap menerima premis bahwa negara adalah aktor utama. Dalam buku mereka yang berjudul “Power and Interdependence” (1977), mereka memperkenalkan konsep interdependensi kompleks, yang menyatakan bahwa negara-negara saling terhubung dalam banyak isu non-keamanan (ekonomi, lingkungan, dll).
Robert Keohane, secara khusus memperkuat kerangka neoliberalisme institusional dalam bukunya “After Hegemony”(1984), dengan argumen bahwa institusi internasional (seperti PBB, WTO, IMF) dapat membantu negara bekerja sama meski tidak ada otoritas global.
Fenomena My First Country di Indonesia
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia juga menunjukkan gejala nasionalisme ekonomi. Contoh utamanya adalah kebijakan hilirisasi sumber daya alam , seperti larangan ekspor bijih nikel. Tujuannya adalah meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan mengembangkan industri pengolahan.
Namun, kebijakan ini menuai gugatan dari Uni Eropa di WTO karena dianggap melanggar prinsip perdagangan bebas. Di bawah Presiden Prabowo, kemungkinan besar arah kebijakan ini akan diperkuat. Prabowo telah menekankan pentingnya kemandirian pangan, energi, dan pertahanan.
Semua ini merupakan bagian dari "Indonesia First" versi lokal. Namun, tantangannya adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kedaulatan nasional dan keterlibatan global.
Studi Kasus dapat dilihat dari beberapa fakta; Pertama; hilirisasi nikel dan gugatan WTO: Kebijakan larangan ekspor nikel mentah yang dimulai sejak 2020 memicu keluhan dari Uni Eropa. Indonesia kalah di WTO, namun tetap bersikukuh melanjutkan kebijakan tersebut.
Dampaknya adalah potensi pengurangan investasi dari mitra global, tetapi juga peningkatan investasi dari negara-negara seperti Tiongkok yang melihat peluang dalam pembangunan smelter di Indonesia.
Kedua; Ketahanan pangan dan impor beras. Wacana swasembada pangan sering kali diiringi dengan kebijakan pembatasan impor.
Namun kenyataannya, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia tetap harus mengimpor beras untuk menjaga stabilitas harga . Ini menunjukkan bahwa kemandirian absolut sulit dicapai tanpa kesiapan sistem produksi domestik yang memadai.
Ketiga; Industri Pertahanan: Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dan kini Presiden berkomitmen memperkuat industri militer dalam negeri. Namun, alih teknologi dari negara maju sangat penting dan ini membutuhkan diplomasi pertahanan yang aktif.
Keempat; Indonesia first mempunyai berbagai tantangan lain yang harus dihadap dimasa kini dan akan datang dalam bentuk; 1) Resiko isolasionisme. Terlalu fokus pada pembangunan industri dalam negeri bisa menyebabkan isolasi dari pasar global. Hal ini bisa menurunkan daya saing dan akses terhadap teknologi baru;
2) Keterbatasan kapasitas industri domestik Banyak industri lokal belum siap menyerap peran strategis yang sebelumnya diisi oleh aktor asing. Risiko stagnasi dan inefisiensi akan meningkat jika proteksi tidak diiringi dengan penguatan kapasitas.
3) Retaliasi dagang. Negara mitra bisa memberlakukan tarif balasan atau menunda perjanjian perdagangan. Ini dapat merugikan ekspor non komoditas Indonesia yang sedang tumbuh.
Perlunya Nasionalisme Produktif!
Apa yang bisa dilakukan Indonesia agar semangat “My Country First” tidak berubah menjadi jebakan proteksionisme? Salah satunya adalah dengan mengadopsi pendekatan yang disebut sebagai nasionalisme produktif, melalui antara lain; Pertama; Kolaborasi selektif.
Indonesia bisa memilih bidang-bidang strategis yang benar-benar perlu dilindungi, sambil tetap membuka sektor lain untuk investasi asing. Kedua; Multilateralisme strategis: Alih-alih menolak sistem global, Indonesia perlu aktif dalam merumuskan ulang aturan main perdagangan global agar lebih adil. Ketiga; Inovasi dan pendidikan: Proteksi hanya efektif jika dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM dan teknologi lokal.
Pernyataan Presiden Prabowo mengenai fenomena "My Country First" mencerminkan kesadaran bahwa sistem global tengah berubah. Namun, nasionalisme harus dikelola agar menjadi kekuatan, bukan jebakan. Indonesia perlu menavigasi perubahan ini dengan kecerdasan strategis. Menjaga kedaulatan tanpa memutuskan hubungan, melindungi industri tanpa mematikan inovasi, dan mengutamakan rakyat tanpa melupakan dunia.
Di tengah ketidakpastian global, nasionalisme bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung dunia. Prabowo punya peluang besar untuk menjadikan Indonesia tidak hanya kuat di dalam, tapi juga disegani di luar.
(*)