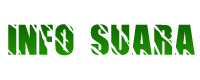Oleh: Diana Triwardhani
Ekonomi digital telah menjadi lokomotif pertumbuhan global dalam dekade terakhir. Perdagangan elektronik, layanan digital, kecerdasan buatan, hingga ekosistem startup telah mengubah wajah perekonomian di banyak negara, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri gencar mendorong transformasi digital melalui berbagai program seperti digitalisasi UMKM, perluasan jaringan internet, dan pelatihan literasi digital.
Namun di balik narasi optimisme ini, masih ada kelompok masyarakat yang tertinggal dan terpinggirkan dari kemajuan digital—yaitu masyarakat di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Ketimpangan digital di wilayah ini menjadi tantangan serius dalam mewujudkan inklusi ekonomi digital yang adil dan berkelanjutan.
Apa Itu Daerah 3T?
Daerah 3T adalah wilayah yang dikategorikan sebagai kurang berkembang karena keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas geografis yang sulit, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, terdapat lebih dari 60 kabupaten/kota yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal pada tahun 2023. Banyak dari daerah ini berada di wilayah timur Indonesia, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.
Kehadiran teknologi digital di wilayah-wilayah ini masih sangat terbatas. Akses terhadap internet, perangkat digital, dan literasi teknologi menjadi persoalan mendasar yang memperlebar kesenjangan antara pusat dan pinggiran.
Ketimpangan Akses Teknologi
Akses terhadap infrastruktur digital adalah fondasi utama dalam pembangunan ekonomi digital. Sayangnya, ketimpangan akses masih mencolok. Menurut laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2023, penetrasi internet nasional memang mencapai lebih dari 78%, tetapi distribusinya sangat tidak merata. Di daerah perkotaan seperti Jakarta, Bandung, atau Surabaya, konektivitas tinggi dan kecepatan internet memadai sudah menjadi hal biasa. Sebaliknya, di daerah 3T, sinyal telekomunikasi seringkali lemah, tidak stabil, atau bahkan tidak tersedia sama sekali.
Hal ini membuat penduduk di daerah 3T kesulitan untuk mengakses layanan digital dasar, seperti pendidikan daring, e-commerce, layanan keuangan digital, atau bahkan informasi publik. Ketika pandemi COVID-19 melanda, ketimpangan ini makin terasa. Banyak siswa di daerah terpencil tidak bisa mengikuti pembelajaran daring karena keterbatasan sinyal dan perangkat.
Rendahnya Literasi Digital
Selain infrastruktur, faktor lain yang menjadi penghambat utama adalah rendahnya literasi digital. Literasi digital mencakup kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan bertanggung jawab. Di banyak wilayah 3T, pemahaman tentang dunia digital masih sangat terbatas.
Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital. Banyak pelaku UMKM lokal yang belum memiliki akses untuk memasarkan produknya secara daring. Masyarakat desa belum terbiasa menggunakan layanan e-banking, e-wallet, atau platform digital lainnya. Padahal, potensi produk lokal dan budaya setempat sangat besar jika dioptimalkan melalui teknologi.
Kesenjangan Ekonomi dan Sosial
Ketimpangan digital berdampak langsung terhadap kesenjangan ekonomi. Mereka yang tinggal di wilayah dengan akses digital tinggi memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan usaha, mendapatkan pekerjaan di sektor digital, dan meningkatkan pendapatan. Sebaliknya, masyarakat 3T cenderung tetap terjebak dalam ekonomi subsisten dengan sedikit peluang untuk berkembang.
Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperdalam ketimpangan sosial antara kelompok masyarakat urban-digital dan masyarakat rural-tradisional. Ketika sebagian besar sektor ekonomi bertransformasi menjadi digital, kelompok yang tertinggal akan semakin tersingkir dari pasar kerja dan peluang ekonomi.
Pemerintah dan Upaya Mengatasi Ketimpangan
Pemerintah Indonesia melalui berbagai kementerian telah menjalankan sejumlah program untuk mengatasi ketimpangan digital, di antaranya:
Pertama : Program Bakti Kominfo: Membangun menara BTS di wilayah 3T dan menyediakan layanan internet gratis di sekolah dan fasilitas umum.
Kedua : Gerakan Literasi Digital Nasional: Memberikan pelatihan literasi digital kepada masyarakat di seluruh Indonesia.
Ketiga : Program 100 Smart Village: Mendorong digitalisasi desa melalui penguatan sistem administrasi, pemasaran produk desa, dan pelatihan SDM.
Namun, tantangan di lapangan masih besar. Banyak infrastruktur yang dibangun tidak bisa berfungsi maksimal karena kurangnya perawatan, sumber daya manusia, atau dukungan sistem. Literasi digital juga masih sebatas pelatihan singkat, belum menjadi kurikulum berkelanjutan.
Peran Swasta dan Komunitas
Selain pemerintah, sektor swasta dan komunitas lokal juga memegang peran penting. Perusahaan teknologi bisa menjalin kemitraan dengan desa-desa untuk menyediakan solusi yang sesuai kebutuhan lokal. Misalnya, startup fintech bisa merancang layanan keuangan mikro berbasis aplikasi sederhana yang cocok digunakan oleh petani atau nelayan.
Komunitas digital juga bisa menjadi agen perubahan. Banyak komunitas relawan yang menyelenggarakan pelatihan komputer, coding untuk anak muda desa, atau membantu UMKM lokal go-digital. Pendekatan dari bawah ke atas ini penting untuk menciptakan keterlibatan masyarakat secara aktif.
Teknologi Tepat Guna sebagai Solusi
Salah satu pendekatan yang menjanjikan adalah penggunaan teknologi tepat guna. Ini berarti teknologi yang dirancang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis masyarakat. Di daerah 3T, solusi seperti: Internet satelit untuk wilayah tanpa menara BTS; Platform e-learning berbasis offline; Marketplace lokal berbasis SMS untuk wilayah tanpa internet; dan Aplikasi pertanian digital dengan antarmuka sederhana.
Solusi semacam ini lebih mudah diterima oleh masyarakat karena tidak membutuhkan infrastruktur canggih atau pengetahuan tinggi.
Harapan Menuju Inklusi Digital
Ketimpangan digital di daerah 3T bukan masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, komunitas lokal, dan masyarakat itu sendiri. Yang paling penting adalah komitmen untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak meninggalkan siapa pun.
Pembangunan ekonomi digital yang adil berarti membangun infrastruktur yang merata, meningkatkan kapasitas masyarakat, dan menyediakan teknologi yang relevan. Bukan hanya membangun menara, tetapi juga membangun manusia.
Transformasi menuju ekonomi digital harus dilihat sebagai peluang kolektif, bukan hanya bagi mereka yang berada di pusat-pusat kota. Masyarakat di daerah 3T memiliki potensi luar biasa yang bisa dikembangkan jika diberikan akses dan kesempatan yang setara.
Ketimpangan digital bukan hanya soal teknologi, tetapi soal keadilan sosial dan ekonomi. Maka, pertanyaan yang harus terus kita renungkan adalah: dalam laju pesat ekonomi digital ini, siapa yang benar-benar kita ajak maju bersama, dan siapa yang masih tertinggal?
Menjawab tantangan ini adalah langkah penting untuk membangun Indonesia yang inklusif dan berdaya saing di era digital.
Penulis, Diana Triwardhani, SE.MM., Ph.D adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN Veteran Jakarta