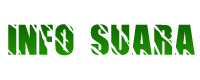Oleh : Dr. Arsalim (Dosen Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Sulawesi Tenggara)
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID-Ketika Nadiem Makarim diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 2019, harapan akan angin segar dalam birokrasi menggema ke seluruh negeri.
Latar belakangnya sebagai pendiri Gojek (startup), simbol transformasi digital, membuat publik membayangkan reformasi radikal dalam dunia pendidikan yang lamban dan tertinggal.
Namun, lima tahun kemudian, nama yang dulu identik dengan inovasi itu justru terseret dalam kasus korupsi senilai hampir Rp 1,9 triliun dalam proyek pengadaan Chromebook. Apa yang salah? Apa pelajaran kebijakan yang bisa dipetik?
Program digitalisasi sekolah, termasuk pengadaan Chromebook senilai Rp9,3 triliun, seharusnya menjadi tonggak penting modernisasi pendidikan Indonesia.
Namun, audit dan penyelidikan Kejaksaan Agung menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang, pengaturan spesifikasi teknis yang mengunci kompetitor, dan dugaan konflik kepentingan yang menjebak sang inovator ke dalam jerat hukum.
Program Chromebook di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim menjadi studi kasus penting soal invasi teknologi dalam sistem pendidikan. Di permukaan, ini tampak seperti lompatan progresif. Jutaan pelajar di daerah terpencil kini bisa mengakses pembelajaran digital. Namun, ketika ditelusuri lebih dalam, kita menemukan dilema klasik yang sering menghantui inovasi public, apakah ini kemajuan, atau bentuk baru dari ketergantungan teknologi?
Dalam teori kebijakan publik, Nadiem dapat dilihat sebagai figur ‘executive entrepreneur’ pemimpin lembaga negara yang membawa semangat inovatif dari sektor swasta ke ruang birokrasi. Teori dari Roberts & King (1989) menyatakan bahwa inovasi sektor publik membutuhkan pemimpin berani, namun harus disertai akuntabilitas dan pengawasan.
Kasus Chromebook memperlihatkan sisi gelap dari pendekatan inovasi. Ketika pemusatan kekuasaan kebijakan, akses eksklusif terhadap vendor seperti Google, dan minimnya transparansi berkelindan menjadi ladang korupsi.
Sektor publik berbeda dengan dunia startup. Di dunia swasta, cepat berarti unggul. Di birokrasi, cepat tanpa transparansi berarti bencana. Keputusan Nadiem untuk mengunci spesifikasi pengadaan hanya pada Chromebook, meski berdalih efisiensi, sejatinya menutup ruang kompetisi yang sehat. Inovasi menjadi alat legitimasi keputusan politik, bukan solusi publik yang inklusif.
Berkaca dari kasus Nadiem dan Chromebook ada beberapa point penting yang menjadi bahan analisis; Pertama; Ketergantungan vendor. Monopoli berkedok Inovasi, dimana pengadaan Chromebook dirancang secara teknis sedemikian rupa sehingga spesifikasinya hanya dapat dipenuhi oleh satu vendor, yaitu Google. Ini menghapus kompetisi terbuka dan menciptakan situasi vendor lock-in, di mana ekosistem pendidikan nasional terikat pada satu perusahaan asing.
Dampaknya jangka Panjang. Bisa saja data pelajar Indonesia, kurikulum, bahkan infrastruktur pembelajaran digital, menjadi bergantung pada logika dan kebijakan korporasi global yang tidak tunduk pada kontrol negara.
Kedua; Digitalisasi tanpa demokratisasi. Alih-alih memberdayakan sekolah untuk memilih solusi teknologi sesuai kebutuhan local. Kebijakan dengan melakukan sentralisasi besar-besaran melalui pengadaan Chromebook menunjukkan bahwa sekolah tidak dilibatkan dalam proses seleksi teknologi, tidak diberi ruang eksperimen, dan diposisikan sebagai “konsumen kebijakan alih-alih sebagai “aktor inovasi”. Ini bertentangan dengan semangat Merdeka Belajar yang diusung Nadiem sendiri.
Ketiga; Resiko privatisasi layanan publik. Ketika platform milik korporasi asing masuk ke dalam jantung sistem pendidikan nasional, kita menghadapi privatisasi diam-diam terhadap layanan publik. Bukan hanya perangkat keras, tapi juga software, sistem akun pelajar, sistem evaluasi, bahkan cara berpikir siswa semuanya mulai diarahkan oleh desain produk perusahaan teknologi, bukan oleh kurikulum nasional.
Keempat; Inovasi tanpa evaluasi etis. Dalam etika kebijakan publik, semua inovasi harus diuji tidak hanya dari sisi efisiensi, tetapi juga dari segi keadilan, kedaulatan, dan keberlanjutan. Kebijakan Chromebook tidak melewati proses evaluasi etis atau partisipatif.
Tidak ada diskusi publik terbuka soal risiko keamanan data, inklusi digital, atau diversifikasi teknologi. Inilah contoh nyata di mana kecepatan inovasi mengalahkan kehati-hatian kebijakan. Inovasi teknologi dalam pendidikan semestinya bukan sekadar soal membawa gadget ke ruang kelas, tapi harus menjawab pertanyaan besar; Siapa yang diuntungkan? Siapa yang mengendalikan? Dan siapa yang bertanggung jawab? Kasus Nadiem menunjukkan bahwa inovasi yang tidak disertai etika, pengawasan, dan akuntabilitas publik justru bisa memperdalam ketimpangan dan mengancam kedaulatan digital bangsa.
Kasus Nadiem Makarim bukan sekadar tragedi personal, melainkan peringatan keras bahwa inovasi bukan jaminan kebajikan. Inovasi butuh transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Tanpa itu, jargon reformasi hanyalah topeng bagi penyimpangan. Mari kita ubah cara pandang terhadap inovasi public, bukan sebagai ‘jalan cepat’ ke solusi, tapi sebagai proses kolektif yang berakar pada integritas.
Pertanyaan yang menjadi catatan sari kasus tersebut adalah “apakah ini kesalahan individu atau indikasi lemahnya tata kelola pemerintahan digital”? Kita tidak bisa mengandalkan integritas personal semata. Kita perlu sistem checks and balances yang kuat termasuk partisipasi publik, audit independen, dan regulasi teknologi yang lebih adaptif. (*)
Ikuti KENDARI POS di Google News
Dapatkan update cepat dan artikel pilihan langsung di beranda Anda.