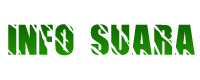Oleh: Dr. Aswin Rivai, SE.,MM
Upaya Donald Trump untuk mereindustrialisasi perekonomian Amerika Serikat melalui penghapusan defisit perdagangan memang menimbulkan dampak besar dan gangguan struktural. Namun, yang lebih penting adalah menyadari bahwa kedua partai besar di AS, baik Demokrat maupun Republik, telah meninggalkan prinsip perdagangan bebas demi tujuan serupa: membangun kembali basis industri domestik. Pergeseran paradigma ini bukan sekadar manuver politik sesaat, tetapi merupakan respons terhadap kegagalan struktural global yang melibatkan ketidakseimbangan neraca transaksi berjalan dan dominasi dolar sebagai mata uang cadangan dunia.
Artikel ini menganalisis penyebab pergeseran kebijakan perdagangan di AS, motif ekonomi di balik kebijakan proteksionis, serta dampaknya terhadap tatanan global. Selain itu, artikel ini akan mengusulkan implikasi kebijakan yang relevan bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang rentan terhadap perubahan struktural global.
Pada Pilpres 2016, baik Donald Trump maupun Hillary Clinton menolak Kemitraan Trans-Pasifik (TPP). Penolakan ini merupakan sinyal jelas bahwa AS mulai meninggalkan semangat perdagangan bebas. Setelah terpilih, Trump langsung memberlakukan tarif impor terhadap produk dari Tiongkok dan negara-negara lain. Kebijakan ini, meski dikritik luas, tetap dipertahankan dan bahkan diperluas oleh pemerintahan Joe Biden. Biden meluncurkan Inflation Reduction Act yang memberikan subsidi besar bagi sektor energi hijau dan manufaktur dalam negeri, disertai proteksi tarif yang sebelumnya diberlakukan oleh Trump.
Dengan kata lain, agenda reindustrialisasi tidak eksklusif milik Trump atau Partai Republik. Kedua partai kini melihat bahwa proteksionisme merupakan instrumen utama untuk mengembalikan posisi AS sebagai negara industri manufaktur.
Menurut John Maynard Keynes, semua negara secara naluriah lebih menyukai menjadi pengekspor bersih daripada pengimpor bersih. Negara-negara eksportir utama seperti Jerman, Tiongkok, dan negara-negara Teluk menyimpan surplusnya dalam bentuk dolar karena tidak bisa menyerapnya di dalam negeri tanpa menaikkan upah dan harga, yang justru akan menurunkan daya saing mereka. Akibatnya, mereka membeli surat utang pemerintah AS, terutama Treasury Bills, yang memberi bunga rendah dan jarang ditebus.
Selama 40 tahun terakhir, AS dapat mengimpor apa saja dengan ‘mencetak’ janji utang digital yang dibeli oleh negara-negara eksportir. Sistem ini memungkinkan AS hidup di luar batas neraca transaksi berjalan. Namun, menurut Michael Pettis dan Matthew Klein, ketergantungan pada defisit transaksi berjalan membawa biaya jangka Panjang yaitu, negara eksportir mengalami stagnasi upah dan investasi domestic dan Ameruka sendiri mengalami deindustrialisasi karena membanjirnya barang murah impor.
Perbandingan struktur ketenagakerjaan AS dari 1975 ke 2025 mencerminkan tren ini. Tiga pemberi kerja terbesar pada 1975 adalah Exxon, GM, dan Ford semuanya perusahaan manufaktur. Sementara pada 2025, Walmart, Amazon, dan Home Depot mendominasi semua perusahaan ritel yang menjual barang impor.
Dolar AS selama ini disebut memiliki “exorbitant privilege” karena perannya sebagai mata uang cadangan global. Namun kini, banyak pembuat kebijakan AS menganggap keistimewaan ini sebagai beban. Ketergantungan pada ekspor dolar berarti AS harus terus menjalankan defisit, yang berarti menekan industri domestik dan menaikkan pengangguran struktural.
Kebijakan reindustrialisasi yang bersifat proteksionis sebenarnya merupakan upaya menekan permintaan global terhadap dolar. Ini hanya dapat berhasil jika negara-negara eksportir seperti Tiongkok dan Jerman mau meningkatkan konsumsi domestik dan menurunkan ketergantungan pada ekspor.
Tanda-tanda rebalancing global sudah terlihat. Mesin ekspor Jerman mulai melambat bahkan sebelum pandemi. Jerman kini melonggarkan aturan debt brake untuk memungkinkan investasi domestik. Negara-negara Uni Eropa meningkatkan anggaran pertahanan akibat tekanan dari Trump. Tiongkok mulai menyadari batas dari strategi ekspor hijau (kendaraan listrik, panel surya, dll) dan mengalihkan fokus ke konsumsi dalam negeri. Negara-negara Asia lainnya seperti Vietnam dan Korea Selatan mendirikan pabrik di AS untuk mempertahankan akses pasar. Semua tren ini mengarah pada dunia yang lebih berimbang, di mana permintaan terhadap dolar global akan menurun.
Implikasi Kebijakan
Indonesia sebagai negara berkembang perlu merespons pergeseran global ini dengan strategi yang tepat agar tidak tertinggal atau terdampak negatif. Beberapa implikasi kebijakan diantaranya, pertama, Diversifikasi Mitra Dagang dan Fokus Pasar Domestik Indonesia harus mengurangi ketergantungan pada pasar AS dan Tiongkok sebagai tujuan ekspor. Diversifikasi pasar ekspor ke Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan akan mengurangi risiko eksternal.
Pada saat yang sama, perlu penguatan konsumsi domestik melalui insentif fiskal dan program inklusif. Kedua, Strategi Industrialisasi Berbasis Nilai Tambah Dengan melemahnya daya tarik global terhadap perdagangan bebas, Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan industri manufaktur berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan. Hilirisasi nikel dan bauksit harus disertai dengan pengembangan manufaktur komponen teknologi seperti baterai dan kendaraan listrik. Ketiga, Reformasi Kebijakan Investasi Asing Dalam konteks reindustrialisasi global, Indonesia harus menjadi tujuan investasi langsung asing (FDI) dengan memberikan insentif bagi sektor strategis, seperti teknologi hijau, otomotif, dan pangan berkelanjutan.
Skema kemitraan strategis perlu difokuskan pada transfer teknologi dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal. Keempat, Penguatan Rupiah dan Manajemen Valuta Asing Jika permintaan global terhadap dolar menurun, Indonesia perlu menyiapkan strategi penguatan mata uang lokal. Ini bisa dilakukan melalui penyediaan pasar keuangan yang dalam dan stabil, serta dukungan kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi. Kelima, Ketahanan Ekonomi Digital dan Sistem Pembayaran Regional Indonesia harus mempercepat digitalisasi ekonomi, termasuk sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code dan mata uang lokal (LCT).
Sistem ini akan mengurangi ketergantungan pada dolar dan meningkatkan efisiensi transaksi regional. Keenam, Pendidikan dan Pelatihan untuk Transformasi Industri Pemerintah harus memperkuat pendidikan vokasional dan pelatihan keterampilan baru untuk menyesuaikan tenaga kerja dengan kebutuhan industri yang sedang tumbuh, terutama dalam bidang teknologi, robotik, dan energi terbarukan.
Reindustrialisasi AS dan penolakan terhadap perdagangan bebas bukanlah anomali, melainkan koreksi terhadap sistem global yang timpang. Dunia sedang bergerak menuju struktur yang lebih seimbang, dengan konsumsi domestik yang lebih tinggi dan ketergantungan yang lebih kecil pada dolar AS. Indonesia harus melihat perubahan ini sebagai peluang untuk memperkuat struktur ekonominya, bukan hanya bertahan dari dampaknya.
Kebijakan yang adaptif, pro-investasi, dan berbasis transformasi struktural menjadi kunci agar Indonesia dapat menjadi pemain utama di era baru perdagangan global yang lebih berimbang dan berdaulat.
Penulis, Dr. Aswin Rivai, SE.,MM, Pemerhati Ekonomi Dan Dosen FEB-UPN Veteran, Jakarta