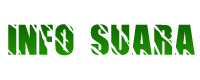Oleh: Linda F Saleh (Kabid Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Sultra)
Kendaripos.co.id -- Sejak UNESCO menetapkan Batik Indonesia sebagai Warisan Budaya Takbenda pada 2 Oktober 2009, batik tidak lagi sekadar sehelai kain. Ia diakui sebagai sistem pengetahuan, simbolisme, dan teknik pewarnaan yang erat kaitannya dengan siklus hidup masyarakat, mulai dari kain gendong bayi hingga kain penutup jenazah. Penetapan ini memicu lahirnya Hari Batik Nasional yang setiap tahun dirayakan pada 2 Oktober, menjadi momentum kebanggaan sekaligus pengingat akan kekayaan budaya yang kita miliki.
Di balik nilai budaya, batik juga menyimpan kekuatan ekonomi. Data Kementerian Perindustrian mencatat bahwa ekspor batik pada tahun 2020 mencapai 532,7 juta dolar AS. Pada kuartal pertama tahun 2021, nilai ekspornya berada di angka 157,8 juta dolar AS. Namun, geliat pasar global yang fluktuatif juga memengaruhi batik. Pada kuartal kedua tahun 2024, ekspor batik turun sebesar 8,39 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh pengaruh geopolitik dan persaingan dengan produk impor, terutama dari China yang memproduksi kain tradisional serupa. Angka ini menunjukkan betapa batik bukan hanya pusaka budaya, tetapi juga komoditas kreatif yang rawan menghadapi dinamika pasar dunia, sehingga membutuhkan strategi perlindungan dan pengelolaan yang adaptif.
Dalam kerangka hukum, batik menempati posisi unik karena berada di persimpangan antara kekayaan intelektual individual dan kekayaan intelektual komunal. Pada satu sisi, para perajin, desainer, dan pelaku usaha batik menghasilkan ciptaan baru berupa motif, komposisi warna, tata letak ornamen, bahkan merek dagang. Ciptaan ini dapat dilindungi melalui instrumen Hak Cipta, Desain Industri, dan Merek. Di sisi lain, motif-motif tradisional yang telah hidup lintas generasi seperti parang, kawung, atau motif khas suatu daerah masuk dalam kategori Ekspresi Budaya Tradisional yang bersifat komunal, sehingga membutuhkan skema perlindungan berbeda.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara tegas memasukkan seni batik sebagai salah satu karya seni rupa yang dilindungi. Perlindungan berlaku otomatis begitu karya dituangkan dalam bentuk nyata. Namun, pencatatan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tetap disarankan sebagai bukti otentik apabila terjadi sengketa. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyediakan payung hukum lain. Merek melindungi tanda pembeda yang digunakan pelaku usaha batik, sedangkan Indikasi Geografis melindungi reputasi dan kualitas yang terkait erat dengan asal-usul geografis suatu produk.
Selain perlindungan individual dan berbasis merek, negara juga mengakui kekayaan intelektual komunal yang mencakup ekspresi budaya tradisional. Permenkumham Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal mewajibkan inventarisasi pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi Indikasi Geografis. Hal ini diperkuat lagi oleh PP Nomor 56 Tahun 2022 yang memperjelas tata kelola kekayaan intelektual komunal. Skema ini penting untuk mencegah privatisasi motif tradisional oleh individu atau korporasi, sekaligus memastikan manfaat yang adil bagi komunitas pemilik warisan budaya tersebut.
Perlindungan kekayaan intelektual untuk batik memiliki arti penting. Pertama, perlindungan ini mendorong inovasi berkelanjutan. Para perajin yang berinvestasi dalam riset pewarna alam, teknik ramah lingkungan, atau pengembangan motif kontemporer membutuhkan insentif ekonomi. Hak Cipta, Desain Industri, dan Merek memberi payung hukum yang jelas untuk lisensi, kolaborasi, dan komersialisasi. Kedua, perlindungan juga memperkuat posisi tawar dalam rantai nilai global. Indikasi Geografis memungkinkan narasi asal-usul yang memperkuat daya saing di pasar dunia, mirip dengan komoditas kopi atau teh. Batik Lasem menjadi contoh bagaimana Indikasi Geografis tidak hanya melindungi reputasi, tetapi juga mendorong promosi destinasi budaya. Ketiga, perlindungan ini menjadi tameng dari risiko cultural misappropriation atau klaim sepihak atas motif tradisional. Dengan adanya inventarisasi kekayaan intelektual komunal, komodifikasi yang merugikan komunitas dapat ditekan.
Bagi pelaku batik, strategi praktis yang bisa ditempuh antara lain dengan memetakan portofolio kekayaan intelektual, membedakan mana yang bersifat komunal dan mana yang individual. Motif tradisional sebaiknya diarahkan pada perlindungan melalui KIK atau Indikasi Geografis, sementara motif baru dapat didaftarkan sebagai Hak Cipta atau Desain Industri. Label dagang atau merek perlu segera didaftarkan untuk mencegah pemboncengan dari pihak lain. Pemerintah daerah bersama komunitas batik juga dapat mendorong percepatan Indikasi Geografis dengan membentuk lembaga pengelola, menyusun buku persyaratan, dan menetapkan mekanisme pengendalian mutu.
Langkah penting lainnya adalah menginventarisasi motif, filosofi, bahan pewarna, dan proses produksi batik. Inventarisasi ini berguna untuk pembuktian asal-usul, dokumentasi, dan pengembangan wisata batik. Di sisi lain, desainer dan UMKM dapat memanfaatkan lisensi motif modern, menjalin kolaborasi edisi terbatas, atau bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam riset pewarna alam. Model bisnis berbasis royalti yang transparan bisa memperluas pasar tanpa melepas kontrol kreatif.
Akhirnya, literasi hukum dan pasar harus dibangun. Fluktuasi ekspor batik menunjukkan pentingnya diversifikasi tujuan pasar, sertifikasi berkelanjutan, serta penguatan branding berbasis cerita. Batik tidak boleh hanya dipandang sebagai produk, melainkan sebagai pengalaman budaya bernilai yang sarat makna.
Batik adalah narasi kebangsaan yang menjelma menjadi kekuatan ekonomi kreatif. Rezim kekayaan intelektual hadir bukan hanya untuk melindungi kepentingan hukum, melainkan untuk memastikan pelestarian berjalan seiring dengan komersialisasi yang adil. Tugas kita adalah merapikan orkestrasi kebijakan melalui inventarisasi KIK, akselerasi Indikasi Geografis, pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual bagi UMKM, dan pembangunan model lisensi yang fair. Dengan demikian, batik akan tetap tegak sebagai identitas budaya yang juga mampu menyejahterakan para penjaganya, dari pembatik rumahan hingga komunitas sentra batik, sambil mengibarkan nama Indonesia di pasar global.
Oleh: Linda F Saleh (Kabid Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Sultra)