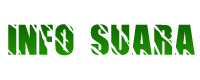Oleh: Baharuddin Yusuf (Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Halu Oleo 2020-2021, Wakil Direktur Kemaritiman Lembaga Parawisata dan Pencinta Alam Mahasiswa Islam
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam 2024-2026)
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Tidak ada kerusakan yang semasif kebohongan. Tidak ada perpecahan yang serusak adu domba. Jika ingin mengukur seberapa dahsyat daya rusak kebohongan, sejarah telah menyajikannya
dengan telanjang. Cukup membuka lembaran kelam menjelang Perang Dunia Kedua: sebuah hoaks tentang tentara Polandia yang disebut-sebut menembak tentara Jerman menjadi pemicu agresi besar-besaran Nazi. Berita palsu itu disebarluaskan secara masif, berulang-ulang, hingga dianggap sebagai kebenaran. Dari sinilah muncul adagium kelam dari Menteri Propaganda Nazi,
Joseph Goebbels: "Ulangilah kebohongan sesering mungkin, maka ia akan menjadi kebenaran."
Narasi ini barangkali terasa jauh, tapi gejalanya kini ada di sekitar kita—bahkan di ruang akademik yang semestinya steril dari dusta. Kita menyaksikan bagaimana kampus, tempat logika semestinya dijaga, justru menjadi ladang subur bagi kabar miring yang belum tentu faktual. Dalam riuh
kontestasi pemilihan rektor Universitas Halu Oleo, nama Prof. Dr. Muhammad Zamrun Firihu (figur yang telah dua periode menakhodai kampus dan membawa UHO menembus 32 besar nasional) menjadi sasaran tuduhan yang entah dari mana asalnya. Dituduh meledak emosinya. Dituduh mengintervensi senat. Dituduh menciptakan ketidaknyamanan dalam proses demokratis. Tapi publik yang jernih justru bertanya: di mana buktinya?
Lebih ironis, kabar ini menyebar bukan melalui mekanisme klarifikasi dan verifikasi, tapi lewat narasi sepihak di media sosial, testimoni tanpa sumber, dan asumsi-asumsi liar. Mengapa kebohongan seperti ini bisa diproduksi dan dipercaya? Karena ia terus diulang. Karena ia memancing emosi. Karena ia menciptakan musuh bersama.
Sepanjang tahun 2024 saja, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat
sedikitnya 1.923 konten hoaks, disinformasi, dan berita palsu yang tersebar di jagat maya
Indonesia. Ini bukan sekadar angka, tapi cerminan bahwa penyebaran informasi menyesatkan bukan lagi insiden acak. Ia telah menjadi strategi komunikasi politik. Upaya sistematis untuk menggiring opini publik agar melihat hanya satu arah, mendukung hanya satu narasi, dan menolak kompleksitas.
Sayangnya, kampus hari ini tidak kebal dari arus itu. Bahkan dalam ruang ilmiah, narasi palsu bisa tumbuh jika kita malas berpikir dan terlalu cepat menyimpulkan. Tuduhan terhadap Prof. Zamrun tampaknya lebih mencerminkan kerapuhan nalar publik ketimbang kesalahan personal. Kampus
yang seharusnya menjadi penjaga nalar justru terjebak dalam dramaturgi sosial: menonton,
berspekulasi, lalu menyebarkannya seolah-olah itu fakta.
Pierre Bourdieu, dalam Homo Academicus, telah menjelaskan bahwa kampus bisa menjadi arena perebutan kekuasaan simbolik yang menyamar dalam bahasa intelektual. Ketika kampus tidak mampu menahan arus opini emosional yang tidak berbasis data, ia sedang menurunkan martabatnya sendiri. Lebih tragis lagi, ketika ruang akademik justru ikut memproduksi hoaks, bukan melawannya. Padahal, seperti diingatkan Hasan Abu Amar dalam Ringkasan Logika Muslim, perasaan tidak dapat dijadikan tolok ukur yang stabil. Perasaan bisa berubah-ubah, sedangkan kebenaran membutuhkan dasar yang konsisten: akal sehat, data, dan logika.
Rasionalitas yang seharusnya menjadi identitas kampus, justru dikalahkan oleh retorika murahan. Antonio Gramsci menyebut hal ini sebagai “hegemoni kultural”—di mana kekuasaan membentuk kesadaran masyarakat sedemikian rupa hingga kebohongan pun diterima sebagai kebenaran,
selama ia disampaikan dengan cukup meyakinkan.
Seperti yang juga ditulis Hannah Arendt dalam esainya Truth and Politics, kebenaran itu rentan— dan ketika ia dikorbankan atas nama emosi atau kepentingan, maka peradaban ikut runtuh bersamanya.
Kampus harus menjadi oase akal sehat, bukan panggung propaganda. Jika tidak, maka kita hanya mencetak generasi yang pandai berselancar dalam opini, tapi lumpuh dalam berpikir. Melawan hoaks adalah jihad intelektual kita hari ini—bukan demi kemenangan politis, tetapi demi
menyelamatkan nalar kolektif dan martabat kemanusiaan itu sendiri.
Kita tidak sedang membela siapa-siapa. Ini bukan soal membela Prof. Zamrun atau bukan. Ini tentang bagaimana kita memperlakukan informasi, bagaimana kita menjaga ruang akademik dari
kontaminasi kebohongan. Sebab jika kampus tidak bisa menjadi tempat yang jernih, lalu di mana lagi nalar akan tumbuh?
Tentu, kritik terhadap pemimpin adalah bagian dari demokrasi. Tapi kritik harus berakar pada data, bukan dendam. Ia harus dilandasi kejujuran intelektual, bukan ambisi politik. Dan ini penting untuk ditegaskan: membiarkan tuduhan tanpa verifikasi berkembang liar bukan hanya merusak
nama orang, tapi merusak institusi itu sendiri. Jika hari ini Prof. Zamrun bisa dicemari tanpa
pembuktian, maka esok lusa siapa pun bisa menjadi korban—terutama mereka yang berani berbeda.
Sebagaimana ditegaskan oleh Edward Said dalam bukunya Representations of the Intellectual, tugas intelektual adalah mengganggu narasi dominan yang tidak berdasar. Bukan ikut menari di
atasnya. Maka pertanyaannya: siapa yang berani tampil rasional di tengah euforia tuduhan hari ini?
Kebenaran memang tidak butuh pembela emosional. Ia butuh ruang yang sehat untuk tumbuh. Dan kampus adalah lahan terakhir bagi nalar untuk tetap hidup — selama kita tidak membunuhnya dengan keyakinan yang sembrono.
“Opini bisa diproduksi massal, tapi kebenaran hanya bisa ditemukan dengan kerja sunyi dan
nalar yang jernih.”