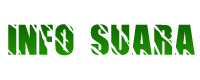Oleh: Dr Fachru Nofrian
Dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi pemerintah memutar arah pembangunan seakan terlihat menjadi lebih industri. Sekian lama diabaikan dan dianggap sebagai beban, industri menampakkan dirinya kembali seperti melawan mitos industri yang tidak mungkin sebagai penggerak pertumbuhan. Hal itu dibuktikan oleh Tiongkok. Ketika semua negara mengabaikan industri, Tiongkok diam-diam mengembangkannya melalui industrialisasi dan membuat Amerika Serikat tersentak.
Tarif dagang melejit tajam seakan menumerisasi besarnya keterkejutan tersebut. Sebetulnya ini bukan kebijakan baru, hanya saja ia telah kembali menjadi penting. Ilmu ekonomi telah menjelaskan ini sejak lama.
Dr Boucher (2019) menyebutkan Trump sebagai Bapak Tarif dan simptom abad ini yang membuat kita perlu mencari tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Data menunjukkan tingkat keuntungan Amerika Serikat terus melambat, sedangkan Tiongkok terus mempercepat. Tingkat keuntungan menjelaskan adanya proses industrialisasi di suatu negara terjadi atau tidak. Sejak tahun 2000, Beijing dan Shanghai terkesan mengambil peran New York dan Washington sebagai pusat perhatian dunia dan berlanjut dengan perang dagang yang semakin frontal misalnya saja antara Amerika Serikat dan Huawei. Perang dagang semakin menguat hingga mencapai klimaksnya ketika Trump menetapkan tarif ke berbagai negara termasuk sahabat-sahabatnya dan mereka yang loyal kepada Amerika Serikat. Pada akhirnya, perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok meluas ke semua negara ibarat Perang Dunia I dan II, termasuk Indonesia.
Politik Dagang Trump si “Bapak Tarif”
Sebagaimana diketahui, Trump menerapkan tarif yang bervariasi terhadap produk berbagai negara yang akan dikonsumsi oleh pasar Amerika Serikat. Diketahui tarif terendah sebesar 10% dan tertinggi di ASEAN hingga 40% yang dikenakan terhadap Myanmar dan Laos. Tiongkok sendiri dikenakan tarif sebesar 30% berdasarkan data bulan Agustus 2025, sedangkan Indonesia sebesar 19%. Selain Tiongkok, negara BRICS lainnya India dikenakan tarif sebesar 25% yang dapat dikategorikan cukup tinggi, namun masih di bawah Brasil sebesar 50%. Afrika Selatan dikenakan sebesar 30%. Di antara negara maju, Uni Eropa sebesar 15%. Tarif tersebut merupakan tarif baru setelah berbagai pemimpin negara bernegosiasi dengan Trump. Sebelumnya, pengenaan tarif lebih tinggi yaitu Indonesia hingga 32%, Tiongkok 145%, India 26%, Laos 48%, Myanmar 49%, Jepang 24% dan Singapura 10%.
Perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat
Data menunjukkan bahwa Amerika Serikat merupakan negara mitra dagang terbesar kedua Indonesia, setelah Tiongkok, namun di atas Jepang, India, Malaysia, Singapura dan Filipina. Jumlah ekspor Indonesia ke Amerika Serikat tahun 2023 sebesar USD23,163,130,000, sedangkan ke Tiongkok sebesar USD64,769,663,000, lalu berurutan ke Jepang USD20,654,400,000, India USD 20,269,352,000, Malaysia USD11,815,815,000, Singapura USD 11,668,197,000, Filipina USD 11,028,339,000.
Pada tahun yang sama, impor ke Indonesia terbesar pertama dari Tiongkok sebesar USD60,075,752,000, diikuti oleh Singapure USD20,479,833,000, lalu Jepang USD16,493,891,000, Amerika Serikat USD11,483,028,000, Korea Selatan USD10,744,900,000, Malaysia USD10,347,081,000, Thailand USD9,970,092,000, Australia USD9,284,037,000, India USD6,407,195,000.
Dalam jangka panjang, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat mengalami peningkatan antara tahun 1998 dan 2023 dari USD7,031,000,000 menjadi sebesar USD23,246,000,000. Seiring dengan itu, impor juga meningkat dari USD3,517,000,000 menjadi USD11,277,000,000. Dalam jangka tersebut, tingkat pertumbuhan ekspor melaju lebih lambat sebesar 6% secara rata-rata dibandingkan impor sebesar 7%. Oleh karena itu, meskipun nilai impor lebih kecil dibandingkan ekspor, tetapi kenaikan nilai impor itu melaju lebih cepat. Ini menjelaskan bahwa meskipun nilai ekspor lebih tinggi daripada impor dan menghasilkan surplus, tetapi sebetulnya posisi ekonomi Indonesia sangat rentan dan masih perlu banyak olah raga dalam perdagangan kedua negara itu. Tentu data impor yang melaju lebih cepat itu perlu diperhatikan lebih lanjut karena terkait dengan substitusi impor yang sangat penting untuk industrialisasi.
Industrialisasi Dalam Perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat
Dalam suatu diskusi dengan ekonom Tiongkok di Jakarta, saya menjelaskan tentang industrialisasi di Indonesia dan membandingkan dengan Tiongkok. Dalam diskusi itu, saya banyak bertanya untuk mengkonfirmasi berbagai pertanyaan saya terkait mengapa proses industrialisasi di Tiongkok berhasil. Dia pun menambahkan bahwa memang betul Indonesia belum memiliki industri. Penjelasannya seakan mengkonfirmasi pentingnya substitusi impor untuk mencapai industrialisasi yang dapat menciptakan industri. Penjelasannya mengingatkan penjelasan seorang ekonom Jepang dalam suatu focus group discussion di Jakarta akan hal yang sama tetapi entah mengapa Indonesia tidak pernah menerapkan kebijakan tersebut meskipun dikatakan oleh negara pengekspor terbesar ke Indonesia.
Data memerlihatkan substitusi impor dalam hubungan dagang Indonesia dan Amerika Serikat yang fluktuatif. Meskipun Indonesia mengalami surplus dagang dengan Paman Sam, tetapi rasio impor tersebut terhadap PDB secara rerata hanya sebesr 1.3% dan mengalami penciutan dari sebesar 3.8% tahun 1998 menjadi sebesar 0.8% tahun 2023. Meskipun menciut, substitusi impor cenderung mengalami pelemahan dalam jangka panjang dari sebesar 1.7% tahun 1999 menjadi 0.06% tahun 2023. Dengan demikian, meskipun surplus, tetapi substitusi impor menciut hingga hampir 0% yang berarti proses industrialisasi dalam hubungan dagang dengan negara itu mengalami pelemahan. Hal ini tentu perlu diwaspadai.
Industrialisasi Dalam Hubungan Dagang Dengan Tiongkok
Berbeda dengan Amerika Serikat, ekspor Indonesia ke Tiongkok periode 1998-2023 mengalami kenaikan dari USD1,171,000,000 menjadi USD65,890,000,000. Seiring dengan itu, impor Indonesia dari Tiongkok naik dari USD2,462,000,000 menjadi USD74,447,000,000. Secara total Indonesia defisit meskipun dalam beberapa periode mengalami surplus. Meskipun defisit, sebetulnya ekspor melaju lebih cepat sekitar 20% secara rerata, dibandingkan impor sekitar 17%. Namun demikian, walaupun melaju lebih cepat, substitusi impor melambat dari 0.04% menjadi -1.8%, memerlihatkan deindustrialisasi yang semakin menguat dalam hubungan ekonomi negara tirai angin dengan negara tirai bambu itu.
Perdagangan: surplus atau Industrialisasi
Data memerlihatkan hubungan dagang antara Indonesia dan Tiongkok yang menguat signifikan dan sebaliknya, melambat antara Indonesia dan Amerika Serikat. Keadaan mengejutkan ini tentu bukan sekadar takdir ekonomi yang mesti diterima oleh Amerika Serikat, yang pada akhirnya memberikan perlawanan dengan atau tanpa Trump, baik melalui mekanisme tarif maupun non-tarif termasuk ke Indonesia. Semua itu tentu dalam rangka menempatkan kembali Amerika Serikat pada posisinya sebagai pemilik hegemoni dalam industrialisasi global. Proses ini telah membawa aturan kapital berubah menjadi aturan dagang dalam ekonomi dunia sehingga Indonesia mau tidak mau mesti mengikuti aturan ini namun tidak secara naif.
Kenyataannya, surplus yang diterima oleh Indonesia dalam hubungan dagangnya dengan Amerika Serikat tidak secara otomatis memberikan keuntungan terhadap Indonesia. Posisi negara itu masih sebagai mitra dagang impor terbesar Inondesia. Padahal, industrialisasi Indonesia dalam perputaran barang dan jasa dengan Amerika cenderung nihil. Rencana pemerintah membuka selebar-lebarnya ekonomi domestik kepada Amerika Serikat dengan menghilangkan tarif dan hambatan non tarif dapat menyebabkan diversifikasi impor yang tampak seperti relokasi dari Tiongkok ke Amerika dan justru dapat berdampak buruk terhadap industrialisasi di Indonesia.
Mengabaikan dampak tersebut hanya menjadikan pemerintah terlihat naif karena mengorbankan ekonomi jangka panjang. Bagaimanapun, surplus ekspor tidak sebanding dengan defisit tenaga kerja yang akan terjadi jika kebijakan nol persen tersebut diterapkan. Toh pandemi yang lalu menjelaskan bahwa ekspor bukan segalanya.
Penulis, Dr Fachru Nofrian, Dosen dan peneliti di FEB dan Pusat Kajian Pembangunan Strategis dan Berkelanjutan UPNVJ, Alumnus Maison d’économie de la Sorbonne, Paris, Prancis.