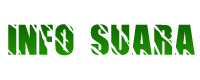KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID--Delapan dekade Indonesia merdeka, namun kemerdekaan itu masih terasa tertahan di balik meja-meja pelayanan publik. Ketika upacara di Istana Merdeka dan di seluruh wilayah menjadi ajang kebanggaan nasional, birokrasi di lapangan justru kerap dipenuhi antrean panjang, prosedur berbelit, dan rasa frustrasi warga.
Pada usia 80 tahun, Indonesia sudah merdeka secara politik dan simbolik, berdaulat, berkonstitusi, berupacara. Namun kemerdekaan substantif yaitu kebebasan warga untuk mengakses hak dasar secara mudah, cepat, dan adil, masih belum merata. Inilah paradoksnya, negara kuat tampil di panggung seremoni, tetapi sering tersendat ketika warga berhadapan dengan meja pelayanan publik.
Menurut laporan Corruption Perceptions Index (CPI) 2024 dari Transparency International, Indonesia mendapat skor 37 dari 100, menempatkannya di peringkat 99 dari 180 negara setara dengan Argentina dan Maroko. Ini menandakan bahwa masalah korupsi dan tata kelola publik masih mengakar kuat.
Di tingkat regional Asia Pasifik, rata-rata skor adalah 44, sedangkan rata-rata global adalah 43. Kementerian PANRB melaporkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara nasional mencapai rata-rata 3,53 dari skala 4. Angka ini terbilang cukup tinggi, namun realitas di lapangan menunjukkan banyak unit layanan publik belum mencapai predikat 'prima'. Mayoritas unit pelayanan masih berjuang melalui evaluasi berkala dengan rata-rata skor hanya 3,08 di provinsi dan kabupaten/kota.
Fenomena ini menggambarkan adanya kesenjangan antara simbol kemerdekaan dan substansi pelayanan publik. Menurut teori Good Governance, prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi seharusnya diwujudkan bukan hanya dalam retorika politis, tetapi juga dalam layanan sehari-hari.
Max Weber dalam teorinya tentang birokrasi menggambarkan model ideal yang rasional, impersonal, dan berbasis aturan. Namun birokrasi Indonesia masih kerap terjebak dalam pola neo-patrimonial di mana kedekatan personal dan patronase politik mempengaruhi pelayanan.
Di hampir semua daerah di Indonesia, dibuat Mall Pelayanan Publik (MPP) untuk memudahkan pelayanan publik kepada masyarakat. Misalnya melalui konsep dynamic governance yang mencakup digitalisasi layanan (Thinking Ahead), evaluasi berkala (Thinking Again), dan kolaborasi antar-instansi (Thinking Across).
Temuannya menunjukkan bahwa meski ada inovasi seperti antrean online dan loket prioritas, integrasi layanan belum optimal dan sosialisasi layanan masih terbatas. Hal ini menggambarkan bahwa inovasi struktural belum diimbangi dengan transformasi budaya kerja dan infrastruktur yang memadai.
Masalah utama pelayanan publik di Indonesia tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga pada kultur birokrasi. Reformasi birokrasi seringkali berhenti pada perubahan prosedur administratif tanpa perubahan pola pikir aparatur. Hal ini menyebabkan program digitalisasi, seperti e-government, hanya menjadi simbol modernisasi tanpa benar-benar memberikan kemudahan signifikan bagi masyarakat. Selain itu, lemahnya pengawasan internal dan eksternal membuat praktik maladministrasi sulit diberantas.
Ombudsman RI mencatat, jenis maladministrasi yang paling sering terjadi adalah penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, dan penyalahgunaan wewenang.
Dalam perspektif ekonomi politik, buruknya layanan publik juga berhubungan dengan tingginya biaya politik. Kepala daerah dan pejabat publik yang terpilih melalui proses politik yang mahal seringkali terjebak dalam siklus pengembalian modal politik.
Hal ini berdampak pada orientasi kebijakan yang tidak fokus pada pelayanan publik, melainkan pada proyek-proyek yang menguntungkan secara finansial bagi kelompok tertentu. Fenomena ini semakin menguatkan apa yang disebut sebagai 'paradoks kemerdekaan' negara merdeka secara politik, tetapi belum sepenuhnya merdeka dalam memberikan hak-hak dasar warganya.
Dimana wajah paradoknya? Gejalanya dapat dilihat dari beberapa hal: Pertama; Prosedur digital tapi budaya analog; Digitalisasi layanan publik di Indonesia memang sudah massif dari aplikasi perizinan, antrean daring, sampai tanda tangan elektronik. Namun, budaya kerja birokrasi dan perilaku pengguna (aparatur & masyarakat) masih berbasis pola analog: mengandalkan tatap muka, tanda tangan basah, dan fotokopi dokumen.
Akar masalahnya adalah transformasi setengah jalan dimana digitalisasi dilakukan tanpa perubahan mindset dan SOP. sistem tidak saling terhubung, sehingga verifikasi masih manual serta trust gap: aparat dan warga belum sepenuhnya percaya bukti digital. Contoh: warga mengunggah KTP di aplikasi layanan, tapi tetap diminta membawa fotokopi fisik ke kantor. Dampaknya efisiensi yang diharapkan dari digitalisasi tidak tercapai, justru menambah beban ganda (double work).
Kedua; Aturan Melimpah tapi Kepastian Minim; Indonesia memiliki banyak regulasi, mulai dari UU, PP, Perpres, sampai Perda. Namun, kepastian pelaksanaan sering kabur karena aturan tumpang tindih atau tidak sinkron antara pusat dan daerah.Akar masalah: Over-regulation tanpa harmonisasi. Penegakan hukum yang selektif atau inkonsisten.
Interpretasi aturan yang berbeda di tiap daerah atau instansi.Contoh: pengurusan izin usaha mikro yang menurut Peraturan Pemerintah cukup lewat OSS, tapi di daerah masih diminta dokumen tambahan yang tidak tercantum di regulasi pusat. Dampaknya ketidakpastian hukum memperbesar biaya transaksi, memperlambat investasi, dan menurunkan kepercayaan publik.
Ketiga; Indikator kinerja fokus proses, bukan hasil. Kinerja birokrasi sering diukur dari output administratif (berapa banyak dokumen diproses, rapat dilaksanakan, laporan disusun) ketimbang outcome (manfaat nyata bagi masyarakat).Akar masalahnya adalah sistem penilaian aparatur berbasis kepatuhan prosedur, bukan keberhasilan memberi solusi.
Tidak ada pengukuran dampak layanan pada kesejahteraan masyarakat. Budaya kerja 'asal selesai' (compliance culture) lebih dominan daripada 'hasil optimal' (performance culture).Kinerja terlihat bagus di laporan, tapi warga tetap kesulitan mendapatkan manfaat konkret.
Keempat; Infrastruktur fisik maju tapi akses layanan timpang. Gedung pelayanan, mall pelayanan publik (MPP), dan kantor pemerintahan di kota besar sudah modern. Namun, di daerah terpencil, akses fisik dan digital terhadap layanan publik masih sulit, karena adanya ketimpangan fiskal dan sumber daya antarwilayah. Konsentrasi pembangunan di pusat kota.Infrastruktur digital (internet, jaringan data) yang belum merata.
Contoh: MPP di ibu kota provinsi misalnya memiliki 50 jenis layanan dalam satu gedung, tapi warga pulau terluar harus menempuh perjalanan berjam-jam hanya untuk mengurus akta kelahiran. Ini menunjukkan bahwa kemerdekaan substantif menjadi elitist, lebih mudah dinikmati warga kota besar dibanding warga desa atau pulau terpencil.
Kelima; Antikorupsi Institusional tapi korupsi rutin. Indonesia punya lembaga antikorupsi seperti KPK, Inspektorat, BPK, Ombudsman, dan Bawaslu. Namun, praktik korupsi tetap berulang di level daerah maupun pusat. Publik terkadang menjadi skeptis terhadap efektivitas lembaga antikorupsi, sementara korupsi menjadi budaya transaksional yang normal di birokrasi.
Untuk menjadikan kemerdekaan benar-benar 'hidup' dalam pelayanan publik, beberapa langkah mendesak perlu dilakukan: Pertama, percepat dan lengkapi digitalisasi layanan publik secara terintegrasi antar-instansi. Kedua, perkuat survei eksternal sebagai alat akuntabilitas publik, termasuk publikasi hasil penilaian kinerja secara terbuka. Ketiga, dorong transformasi budaya birokrasi dari orientasi prosedur ke orientasi hasil (outcome). Keempat, bangun komitmen lintas daerah melalui pelatihan, sosialisasi, dan replikasi praktik terbaik.
Delapan puluh tahun kemerdekaan bukan hanya soal perayaan simbolis, tetapi momentum evaluasi substantif. Pertanyaan yang harus dijawab adalah: apakah kemerdekaan kita hanya berhenti pada simbol-simbol seremonial, atau sudah hadir dalam setiap proses pelayanan publik yang mudah, cepat, dan adil? Merdeka sejati adalah ketika rakyat terbebas dari belitan birokrasi dan dapat mengakses hak-haknya tanpa hambatan.