balitribune.co.id | Sebagai sebuah negara demokrasi tentu Pemilu sebagai peranti untuk menyuarakan aspirasi rakyat terhadap negara. Demokrasi, sebagai sistem pranata pemerintahan yang berdasarkan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan tentu ujungnya adalah untuk kesejahtraan rakyat. Hajatan pemilu seharusnya bergembira dalam menyambut pesta demokrasi, layaknya pesta-pesta yang lainnya.
Demokrasi menjadi wahana bagi kebebasan berekspresi gagasan atau menyuarakan gagasan yang dititip melalui wakil rakyat di pemerintahan. Yang mewakili harus menjaga keadaban sebagai negara demokrasi.
Namun, di Indonesia terutama dalam konteks hajatan demokrasi yang disebut Pemilu/Pemilukada, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu menjadi sorotan dan buah bibir di kalangan pemangku kepentingan “politik”. ASN serasa geli, menjadi risih bahkan diambang ketakutan setiap datang pesta demokrasi disebut Pemilu/Pemilukada.
ASN seakan menjadi dongkrak politik untuk mengangkat beban demokrasi yang begitu berat dan agar betul-betul terlihat sebagai negara demokrasi. ASN menjadi pusat perhatian tatkala Pemilu sehingga ASN seperti gadis yang sensitif terhadap rangsangan politik dan terkadang selalu menggoda.
Hak politik dikebiri oleh netralitas tapi kewajiban politik tetap berjalan sesuai fitrah demokrasi sebagai warga negara yang menjungjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Aturan yang selalu kontroversial, khususnya dalam larangan terhadap sembilan pose ASN sepertinya sangat sensitif.
Hal ini memicu perdebatan tentang apakah demokrasi Indonesia terlalu sensitif atau belum dewasa. Jika seandainya pula warna pakaian, gaya swafoto sampai gestur tubuh dalam berpose masih diatur saat jelang Pemilu, pertanda demokrasi Indonesia masih proses pendewasaan dan perlu nutrisi agar cepat tumbuh subur dan dewasa. Jika hal ini terjadi berarti demokrasi kita menjadi beku dan politik menjadi kaku.
Larangan terhadap sembilan pose ASN menjadi cermin kehati-hatian pemerintah dalam menjaga netralitas ASN. Namun, banyak yang berpendapat bahwa kebijakan ini menunjukkan ketidakdewasaan dalam memahami esensi demokrasi. Demokrasi seharusnya bukan hanya tentang melarang pose tertentu, melainkan memberikan kebebasan ekspresi yang lebih luas yang tetap dibingkai oleh aturan. Partai adalah rumah demokrasi tempat berkreasi menuju dedikasi kekuasaan yang bermartabat.
ASN menjadi salah tingkah bahkan ada semacam ketakutan menyambut datangnya pesta demokrasi hanya karena ada pergeseran makna kata netralitas. Jika demokrasi kita terlalu sensitif nanti berpakaian pun orang menjadi takut bahkan bisa jadi pakaian ASN bisa putih dan hitam agar tidak mencirikan warna partai tertentu, ironis. Dagelan politik hanya terjadi pada demokrasi yang belum dewasa.
Analogi demokrasi kita bagai anak kecil yang mudah terpengaruh mungkin mencerminkan kondisi demokrasi saat ini. Seperti anak kecil yang membutuhkan bimbingan, tuntunan agar bisa berjalan tegak dengan politik sebagai penyangga pilar demokrasi. Demokrasi juga perlu diarahkan dan dibimbing dengan aturan yang bijaksana berkeadilan.
Namun, kebijakan yang terlalu membatasi ekspresi ASN dapat dianggap sebagai tindakan paternalistik yang mereduksi demokrasi menjadi sekadar simbol tanpa substansi. Netralitas ASN masih bersifat abu-abu karena ASN masih menentukan sikap sebagai pilihan di bilik suara. Lantas dengan memberikan hak suaranya masih bisa dikatakan netral? Keabu-abuan ini melahirkan sifat yang sensitif sedikit disentuh teransang sehingga terjadi orgasme politik.
Netralitas ASN seharusnya dapat diwujudkan melalui representasi politik yang matang dan dewasa, bukan melalui pembatasan pose atau hanya sebatas gestur sebagai Bahasa tubuh. Demokrasi yang berkualitas seharusnya mampu mengakomodasi beragam ekspresi tanpa mengorbankan ASN dengan dalih netralitas. Jika kita terlalu fokus pada larangan-larangan semacam ini, kita dapat kehilangan esensi sejati dari demokrasi yang memberdayakan individu untuk menyuarakan pendapatnya.
Ilmu tanda “semiotik” bukan milik partai politik tetapi milik semua orang bergantung pada kesepakatan yang bersifat konvensional. Pertanyaannya kemudian adalah sejauh mana kita harus takut dalam membahas isu-isu sensitif dalam konteks demokrasi? Kebebasan berbicara dan ekspresi adalah pilar penting dalam sebuah demokrasi yang matang. Jika kita terlalu takut atau terkekang, demokrasi tersebut bisa menjadi sekadar ilusi tanpa ruang bagi dialog yang sehat dan konstruktif.
Pembelajaran dan Pendidikan demokrasi harus hadir di rumah karakter yang disebut sekolah melalui pemilihan ketua OSIS sebagai ajang Pendidikan demokrasi. Kita tidak boleh alergi berpolitik karena semua bermuara pada kanal-kanal politik. Hadirkan dan perkenalkan demokrasi sehat dan beradab sedini mungkin lewat hajatan pemilihan ketua OSIS di sekolah-sekolah.
Politik adalah sebuah konsep negara yang didalamnya berbicara mengenai kebaikan bersama, keteraturan, kesejahteraan, kebahagiaan dan penyelesaian suatu konflik. Dari politiklah pemimpin dilahirkan, dari politik pula kebijakan ditetapkan, dari politik hukum dirumuskan, dan dari politik pula Pendidikan diformulasikan.
Langkah-langkah yang terlalu berlebihan dalam mengatur ekspresi ASN juga dapat membuka pintu bagi potensi penyalahgunaan kekuasaan. Ketakutan untuk menyebutkan angka 1, 2, dan 3 mungkin menciptakan lingkungan yang tidak sehat, di mana masyarakat menjadi enggan menyuarakan pendapatnya karena takut mendapat sanksi. Demokrasi seharusnya menciptakan ruang bagi dialog terbuka, bukan memupuk ketakutan. Jangan-jangan saat pesta demokrasi tangan menjadi kaku dan angka 1. 2, dan 3 menjadi takut diucap. Jika angka 1,2, dan 3 takut diucap merupakan ciri demokrasi masih balita yang penuh ketakutan.
Lebih lanjut, ASN seolah-olah dikekang dalam simbol partai politik. Hal ini menciptakan suasana di mana netralitas ASN terancam, dan tugas-tugas mereka dapat dipandang sebagai bentuk dukungan terhadap suatu paham politik tertentu. Politik seharusnya mampu berdiri di atas kepentingan partai, dan netralitas ASN seharusnya dijaga tanpa merasa terkungkung oleh simbol-simbol politik tertentu.
Dalam menghadapi tantangan kompleks demokrasi, penting bagi pemerintah untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara menjaga netralitas ASN dan memberikan ruang bagi kebebasan ekspresi. Kebijakan yang terlalu restriktif dapat merugikan dinamika demokrasi dan merugikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan.
Sebagai negara demokratis yang berkembang, Indonesia perlu terus berinovasi dalam merancang kebijakan yang mendukung esensi demokrasi. Bukan hanya melalui larangan-larangan yang bersifat simbolis, tetapi melalui langkah-langkah konkret yang mengukuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokratis. Sehingga, kita dapat melihat demokrasi Indonesia bukan hanya sebagai sistem yang sensitif, tetapi sebagai sistem yang matang, inklusif, dan memberikan kebebasan sejati kepada setiap warganya. Disemogakan demokrasi tumbuh dewasa dan sehat bermartabat.

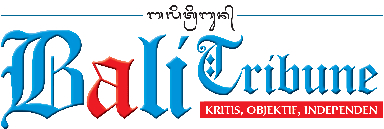 1 week ago
17
1 week ago
17








































